| TagBoard |
arsip

Tuesday, November 12, 2002
Istriku
Istriku seorang penyendiri. Ia berpikir, hanya dirinyalah yang hidup di dunia ini. Mungkin juga ia seorang yang pesimis. Sebagai suami, kadang saya jengkel juga kehadiran saya sering tak dianggap. Seolah kami tidak pernah kawin, ke KUA dan menandatangani surat nikah. Di matanya, saya hanyalah seonggok daging hidup yang jadi teman hidupnya.
"Aku tidak pernah jadi anak-anak," katanya setiap kali kuingatkan sikap dan sifatnya itu salah. Saya sudah bisa menebak maksudnya. Ia begitu tertekan saat sebelum bertemu saya, sebelum kami kawin dan hidup berumah tangga. Ia, sejak dilahirkan, sudah dipaksa berpikir dewasa. Saya tidak tahu definisi dewasa mana yang ia pakai untuk mengatakan itu. Saya juga tidak tahu apa yang dimaksudkannya "dipaksa berpikir dewasa".
Istriku seorang yang merasa bersalah. Seolah dunia ini selalu menunjuk hidungnya sebagai pendosa. Ia jadi pendiam setiap harinya. Hanya kalau saya mengajaknya bicara baru ia mau ngomong. Itu pun hanya sepotong-sepotong saja. Ibaratnya beduk di masjid, kalau tak dipukul, ya, ndak bunyi. Begitupun kalau kami bercinta, sayalah yang memulai dan--terus terang--hanya menikmati sendiri. Karena jika saya tanya istri saya, dia selalu menjawab "tidak tahu" apakah percintaan kami nikmat atau tidak. Saya sudah malas menanyakan dan mencari tahu soal satu ini. Soalnya, itu bisa membikin saya ngamuk di ranjang.
Waktu pacaran, saya berharap sifat dan sikapnya itu berubah setelah kami kawin. Saat itu saya juga sering menasihatinya agar mau mengubah sifat jeleknya itu. Maka kami kawin, karena ia berjanji akan mengubah sifat merasa bersalah itu. Tapi, sampai kami kawin, saya tidak tahu apa yang membuatnya merasa sedemikian bersalah itu. Untuk itu, Ibu, saya kirimkan surat ini.
O, ya, kami sudah kawin lima tahun. Waktu yang lama, ya, Bu. Mungkin Ibu bilang saya suami yang bodoh, sedemikian lama memendam kejengkelan ini. Tapi tidak, Ibu. Saya tidak jengkel dengan kelakuan istri saya itu. Saya mungkin orang yang tidak peduli. Saya hanya ingin menolong derita yang dirasakan istri saya. Ia pernah ngomong jika dunianya itu membuatnya putus asa. "Untung ada kamu," katanya yang membuat saya tersanjung.
Maka, selama lima tahun itu, rumah tangga kami adem-adem saja. Pertengkaran kecil sih ada, tapi itu sih wajar kalau kami sedang capai. Kami sama-sama bekerja. Pergi-pagi-pulang-malam. Kalau hari libur kami memilih untuk tidur seharian di rumah, kadang-kadang juga bercinta sampai saya puas.
Dan kami, selama lima tahun itu, tak berpikir atau menyinggung-singgung soal anak. Waktu pacaran dia sempat ngomong takut punya anak. "Saya ngeri punya anak," katanya. Seorang temannya, punya anak perempuan, dihamili, ditinggalkan pacarnya, lalu dibawa kabur pacar ke duanya. Temannya itu stres memikirkan anak-anaknya yang bandel tak mendengar nasihatnya. Anak laki-lakinya masuk rumah sakit jiwa karena tak kunjung bisa memecahkan rumus matematika yang ia buat sendiri. "Saya tidak mau terbebani oleh anak-anak yang kita harapkan," kata istri saya.
Alasan yang masuk akal. Saya menerima alasan-alasan dan jalan pikirannya, kecuali ya itu tadi: cara memandang dirinya sendiri. Terlihat sepintas rumah tangga kami tak terlihat meneggangkan, runyam atau berujung perceraian. Saya sendiri tidak berharap cerai. Saya malas cari istri lagi. Jika saya mengawini istri saya itu karena memang saya cinta. Maaf, saya tak bisa memberi alasan lebih dari itu untuk menjelaskan kenapa saya mengawininya, hidup berdua dengannya. Saya cinta dia titik.
Dia tak pernah punya target menjalani hidup ini. Baginya hidup ini, ya, apa yang dihadapinya sekarang. Kemarin itu persetan dan masa bodoh dengan hari depan. Menjalani saja. Sementara saya suka bikin rencana ini-itu tentang hidup: punya rumah sendiri, punya mobil, punya perpusatakaan sendiri dan bisa melancong ke pelbagai tempat untuk mengetahui hidup di belahan dunia lain. Dia suka naik gunung, saya juga. Tapi saya lebih sreg jika pergi ke pantai. Maka kalau libur kami suka kemping di gunung atau buka tenda di pantai.
Suatu ketika dia bilang, "Saya hamil." Saya senang mendengarnya. Dia juga sumringah menceritakannya. Langsung saja saya bikin rencana-rencana untuk jabang bayi kelak: nabung untuk masa depannya. Tapi, seperti biasa, dia diam saja. Karena tak ada tanggapan, saya pun diam dan lebih baik mempraktekan saja soal nabung itu daripada diomongin.
Tapi kandungannya keguguran pada minggu ke tiga. Saya sedih, istri saya lebih-lebih. Sedih karena kami gagal punya bayi. Saya sudah membayangkan enaknya jadi bapak. Dipanggil Abah oleh anak saya. Saya cepat-cepat mengubur kesedihan itu, karena saya takut istri saya itu tambah merasa bersalah saja tanpa saya marah karena keguguran itu. Tapi kami tak berusaha agar istri saya hamil lagi. Kami jalani seperti biasa lagi.
Ibu, apa yang terjadi dengan hidup kami ini? Kami tak merasa apa-apa tapi merasakan telah terjadi apa-apa dengan hidup kami. Kami senang menjalani hidup, tapi serasa ada yang kurang dalam keseharian kami, terutama saya. Saya, istri saya, tidak tahu apa yang kurang itu. Kami tak memikirkan uang untuk itu. Gaji kami sudah cukup untuk menanggung hidup berdua.
Jika saya memutuskan mengirim surat ini untuk Ibu, saya hanya ingin berbagi cerita saja. Jika punya waktu Ibu bisa membalas dan memberi jawab surat saya ini. Mungkin kami bukan satu-satunya keluarga di dunia ini yang menjalani dan memandang hidup seperti ini. Sumpah, saya tak terbebani oleh gaya hidup istri saya itu. Saya tidak mau membeberkan masa lalu istri saya untuk menganalisis kenapa dia menjadi seorang yang pendiam, penyendiri dan merasa berdosa seperti itu.
Saya pikir tak ada hubungannya dengan masa kecil atau kehidupan keluarganya. Saya sendiri, sekali lagi, tak tahu persis bagaimana hidup dia waktu kecil. Apakah diamnya itu akan merusak? Saya tidak tahu. Karena selama ini tak ada hal yang rusak oleh sikap diamnya itu. Saya pernah baca buku tentang diam yang merusak tubuh. Tapi si penulisnya hanya ngomongin diam yang menjadi penyakit. Istri saya tidak punya penyakit diam. Dia justru menikmatinya.
Saya, secara diam-diam, pernah minta tolong seorang pintar. Saya berharap orang pintar itu, dengan jampi-jampinya, bisa menyembuhkan istri saya. Si dukun, yang disebut Pak Kyai itu, memberi saya air putih satu gelas. Air itu, kata Pak Kyai, harus disiramkan ke setiap sudut kamar jika magrib datang. Sisanya harus dicipratkan ke ubun-ubun istri saya. Maka kalau malam dan istri saya sudah tidur, sedikit-sedikit saya cipratkan air itu ke rambutnya. Jika dia bangun karena air itu, saya pura-pura membelai rambutnya, mengusap wajahnya, lalu mencium keningnya. Biasanya istri saya tidur lagi tanpa curiga saya menyiramkan air mantra itu.
Tapi lama-lama istri saya tahu kalau saya minta pertolongan dukun. Dia marah. "Buat apa kamu pergi-pergi ke dukun?" katanya, "emang saya gila. Kamu yang gila, percaya sama dukun. Berapa duit yang sudah kamu berikan sama dukun itu?" Saya diam. Mungkin juga saya gila dengan menganggapnya agak gila. Akhirnya saya berhenti pergi ke dukun.
Akhir-akhir ini saya sering memikirkan sikap dan sifat diam istri saya. Bukan apa-apa, saya kok merasa hambar karena seumur kami kawin tak pernah ia cemburu. Padahal, saya juga ingin bertengkar karena dia menuduh saya selingkuh, misalnya. Tapi, dia tidak. Pernah saya bikin skenario. Saya bikin sebuah surat cinta dan menyimpannya di file komputer.
Tapi apa komentar dia sewaktu saya pura-pura lupa menutup layar monitor? Dia bilang, "Sejak kapan kamu tertarik menulis?" yang membuat saya mengerutkan kening. Padahal, ketika istri saya membaca surat cinta gadungan itu, saya mengintip dan menunggu reaksinya. Dia pikir surat cinta itu sejenis cerita pendek yang akan dikirimkan ke koran. Duh, Ibu, mana bisa hubungan yang dingin seperti ini.
Menurut buku priskologi, pertengkaran itu kadang-kadang perlu juga asal tidak kebablasan untuk menumbuhkan gairah. Saya sudah coba pelbagai upaya agar kami bisa bertengkar. Misalnya, saya paksakan untuk selingkuh beneran. Saya lirik teman kerja di kantor. Mula-mula saya ajak makan, lalu nonton dan sering saya beri hadiah-hadiah. Sengaja saya simpan nomor teleponnya dengan dering telepon istimewa dibanding nomor lain yang tersimpan di handphone saya.
Dengan sering makan di luar atau nonton itu saya jadi sering telat pulang ke rumah. Maksudnya, ya itu tadi, memancing agar istri saya marah. Lalu kami bertengkar, dan saya coba merayunya lagi ditambah mengaku bersalah telah selingkuh. Jika sudah begitu, kami berharap hubungan kami menghangat lagi.
Tapi boro-boro marah, duit saya malah habis tidak karu-karuan karena sering nraktir temen saya itu. Istri saya dingin-dingin saja. Dia tahu saya sering makan di luar dengan teman kantor. Apa dia bilang, "Jangan kerja terlalu capai. Nanti sakit." Duh, Ibu, apalagi yang harus saya lakukan untuk menghangatkan hubungan kami ini.
Saya tempuh upaya lain lagi. Misalnya, saya tiba-tiba marah karena tidak suka makanan yang dimasaknya. Saya tuding istrinya sudah tak tahu lagi selera makan suaminya. Bukannya ngambek karena dituding dengan alasan yang tidak jelas, dia malah minta maaf. Dia berjanji akan masak makanan kesukaan saya. Padahal sayur lodeh itu makanan kesukaan saya lho, Bu. Istri saya tahu itu, dan saya mengakui masakannya paling enak di dunia.
Atau saya marah karena dia tak pernah menghabiskan makan malamnya. Dia mengaku sedang tidak enak badan. Dia minta diantar ke dokter. Saya tidak mau. Bukannya ngambek, dia malah pergi sendiri dan pulangnya bawa martabak telor kesukaan saya. Saya pura-pura tidak mau, meski setelah istri saya tidur, martabak itu saya habiskan juga. Lama-lama saya khawatir juga dengan keadaan istri saya itu.
Saya suka memandanginya lama-lama kalau dia sudah pulas tertidur. Saya cari kenangan-kenangan kami sewaktu pacaran. Susah payah saya dapatkan dia untuk jadi pacar sewaktu kuliah. Saya sempat ditolaknya sampai tiga kali. Tapi, mungkin sudah jodoh, kami pacaran juga dan terus kawin. Sampai sekarang, sampai saya heran dengan sikap dan sifat istri saya itu.
Begitulah Ibu. Saya tidak berharap Ibu menanggapi surat saya ini. Bisa dibaca saja sudah syukur. Sekali lagi saya hanya ingin berbagi cerita saja. Kalaupun Ibu punya waktu dan mau menanggapi, ya, silahkan saja, mungkin berguna bagi pasangan lain yang punya cerita hidup seperti kami. Terima kasih.
NY, Jakarta.
****
Dia menuliskan rubrikpsikologi@mediakonsultasi.net di kolom pengiriman. Setelah semua kolom surat elektronik itu terisi, kursor diarahkan ke pranala "Send". Tak lama komputer memberi tahu jika "Your e-mail has been sent." Dia menutup layar monitor laptopnya. Mematikan lampu. Merapikan buku-buku. Ia tertegun di tepi ranjang. Istrinya, di ranjang itu, sudah terbujur menelentang. Ia mencium bibir dan kening si istri dan merebahkan diri di sampingnya. Ia memandangnya lama-lama.
Jakarta, 2002
Bagja
posted by ang 4:28 AM
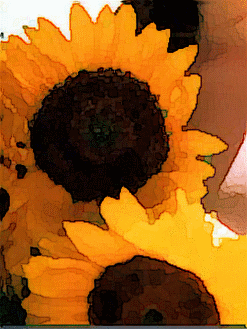
blog TOELIS, diisi oleh beberapa manusia. jika berminat untuk ikut menggunjingkan, menumpahkan, membumikan, atau mengumpatkan apa saja silakan kirim email ke anfus@frogshit.com dengan subject: ruang tulis
