| TagBoard |
arsip

Friday, September 06, 2002
Tinggi-Rendah
Nirwan Dewanto
SEROMBONGAN anak muda dengan rambut warna-warni, anting-anting pada bibir dan hidung, dan pakaian ketat-mencolok, mendatangi aku dan bertanya, "Mengapa engkau tak pernah bicara tentang kebudayaan massa yang kami gandrungi? Mengapa engkau hanya menjunjung kesenian tinggi, wahai penulis angkuh? Lekaslah jawab. Kalau tidak, kami akan membuatmu kian resah!"
Baiklah, wahai anak-anak masa depan. Aku tidak ingin menyenangkan kalian. Inilah jawabanku, mudah-mudahan kalian bisa menganggapnya sebagai buah kejujuran:
AKU menyukai budaya massa, meski lebih tepat kukatakan bahwa dialah lautan yang mengepungku tanpa kukehendaki. Aku tidak memilihnya, dialah yang menangkapku. Setiap saat aku diberondong iklan, video klip, sinetron, lagu pop; terkadang aku takjub juga pada, misalnya, kalimat iklan yang lebih bagus ketimbang puisi. Di masa kanak, aku menyukai komik silat dan superhero (Si Buta dari Gua Hantu, Panji Tengkorak, Gundala Putra Petir, misalnya) di samping majalah anak-anak "serius" Si Kuncung dan Kawanku. Boleh dibilang, minat bacaku tumbuh dari komik.
Aku menonton film Hollywood: terkadang aku berpikir bahwa Hollywood bercerita sebaik juru cerita tradisional, terbalik dengan para novelis sastra yang tak jarang membosankan. Namun Hollywood terlalu sering menjajakan kisah yang teramalkan, pahlawan yang tak ubahnya malaikat, orang jahat yang tak kurang dari iblis: semua itu bukan hanya seperti makanan kaleng, tapi juga mengasingkan kita dari kecerdasan. Itulah sebabnya kini aku mencintai film Iran, Taiwan, Brasil, Polandia, misalnya, yang sama sekali subversif terhadap gaya Hollywood.
Aku percaya, budaya massa berwatak demokratis -- jika "demokratis" itu kita artikan sebagai keterjangkauan dan "kegunaan" bagi semua orang, terlepas dari sentimen etnis, lapisan sosial, keagamaan, maupun kebangsaan. Titik temu selera, pengetahuan, dan kepentingan bersama bukanlah lembaga perwakilan rakyat, melainkan televisi, pusat belanja, dan papan iklan di jalan raya.
Sementara itu kesusastraan, lukisan, musik "klasik", misalnya, tak dengan sendirinya berada di atas. Memang ia berada di lingkup terbatas, di kota-kota besar terutama. Tapi kita tak punya kelas borjuasi (seperti di Barat) yang memang menjadi pelindung utama kesenian modern. Di sini seni rupa, misalnya, hanya terasa "terpencil" atau "tinggi" karena ia hanya menjadi milik pribadi, sementara tak ada koleksi atau museum yang sungguh-sungguh terbuka untuk umum. (Nah, kaum "borjuasi" kita hanya pura-pura modern; bukankah mereka kian terbuka memamerkan watak kampungan sejak jalan raya sampai upacara perkawinan?)
Aku pernah mendengar sejumlah teman berseru bahwa kita harus menggalakkan apresiasi seni, misalnya di sekolah, supaya kesenian tak terpencil lagi. Aku katakan, tidak, sebab kita tak memerlukan apresiasi seni, melainkan kemampuan berpikir dan menyatakan diri, supaya kita tak menjadi paduan suara burung beo. Lebih baik jika kaum seniman mengasah sendiri kemampuan mereka sebab selama ini karya mereka membosankan dan dihantui mediokritas. Mereka hanya mengira karya mereka "modern" dan "tinggi": ya, mereka harus keluar dari lingkup nasional -- artinya, lingkup teman sendiri -- supaya mereka tahu bahwa begitu banyak yang lebih bernas mancanegara.
Aku tak menyukai istilah budaya tinggi untuk jenis kesenian yang kebetulan belum masuk ke arus budaya populer. Setiap bidang modern, entah itu seni atau ilmu atau apa saja pada dasarnya "terpencil" karena ia merupakan spesialisasi. Sebagaimana ilmuwan, seniman memerlukan laboratorium, menara gading, atau apa saja, supaya ia bisa bekerja dengan baik. Namun jika industri kebudayaan berjalan baik, apa yang dihasilkannya akan menjadi produk budaya massa juga. Kita tahu, misalnya, karya Stephen Hawking dan sejumlah ilmuwan "tinggi" bisa dicetak jutaan kopi. Jadi, apa yang elitis dalam kasus demikian?
Pembedaan tajam antara budaya massa dan budaya tinggi di Barat, aku kira, tidak pernah sungguh-sungguh terjadi ketika demokrasi menjadi begitu mapan. Tidak ada elite yang bisa mendesakkan kebudayaan mereka (katakanlah, budaya tinggi) ke massa rakyat; bahkan tak ada produk kebudayaan modern yang khas milik kelas atau kelompok tertentu. Kesenian, sebagaimana produk kebudayaan yang lain, terbuka bagi setiap orang. (Tentu, pada masa sebelum-demokrasi, kita bisa bicara tentang kaum bangsawan dan kemudian kaum borjuis yang bisa memaksakan, dengan kasar atau halus, kebudayaan mereka ke "massa-yang-tak berbudaya.")
Teknologi telah membuat karya seni kehilangan kekudusannya, sebagaimana dikatakan Walter Benjamin lebih dari setengah abad yang lampau. Demikianlah novel serius dari Balzac atau Nabokov akan mematuhi hukum kemasan dan promosi yang sama dengan novel pop yang terbaru. Sebuah lukisan van Gogh direproduksi dalam kartupos, poster, T-shirt, sapu tangan, dan label minuman keras. Dan Che Guevara menjadi ikon pop sebagaimana John Lennon. Demikianlah budaya tinggi sanggup melucuti dirinya sendiri.
Pasar bisa membebaskan produk kebudayaan dari lingkungan asalnya yang terbatas. Dalam contoh di atas, kita melihat produk yang dibebaskan dari lingkaran kaum intelektual, kaum "garda depan". Namun, pasar bisa juga membawa produk kebudayaan dari bawah ke atas, atau dari pinggir ke pusat. Contoh paling klasik adalah musik jazz. Contoh mutakhir sangat banyak: misalnya apa yang disebut world beat yang menampilkan para musisi seperti Youssou Ndour (Senegal) dan Buena Vista Social Club (Kuba). Tidaklah benar bahwa "penciptaan eksperimental" adalah khas budaya tinggi.
Kita patut mengacungkan jempol pada mereka yang menggabungkan diri ke pasar: sebab pasar yang sehat selalu memerlukan produk baru, dan kebaruan ini tak mungkin dicapai tanpa eksperimen dan kreatifitas. Hollywood, industri parfum dan pakaian, iklan, media-massa, indusri mainan kanak-kanak, Disneyland, adalah contoh yang semestinya; juga industri makanan/restoran Jepang, Thai, Vietnam yang sekarang menyerbu Eropa dan Amerika.
Sementara itu, di negeri-negeri yang memisahkan diri dari kapitalisme internasional, misalnya Iran, Kuba, atau Cina, kebudayaan yang dominan tentulah budaya tinggi. Negara menyebarkan "kebudayaan resmi" sebagai "kebudayaan rakyat." Dapur-dapur penciptaan berada dalam pengawasan, bahkan dibiayai oleh, Negara. Seperti halnya pasar dalam kapitalisme, Negara mempunyai kekuatan untuk melakukan penyetaraan cita rasa dan penghancuran hirarki budaya lama.
Bedanya: rejim-rejim otoriter ini berhasil mengembangkan lembaga kesenian, termasuk pendidikan kesenian, yang baik, sehingga pada saatnya akan timbul sebuah generasi-pelawan yang sanggup memberikan alternatif terhadap kebudayaan dominan bukan hanya di negeri masing-masing, tapi juga ke dunia luas. Kita kini mengenal sinema Iran dan Cina Daratan, misalnya, sebagaimana produk (dagangan) penting di Barat, di samping, tentu saja, sebagai harta karun baru khazanah sinema dunia. (Bandingkan dengan perfiman kita yang ambruk setelah dibina hanya dengan seribu aturan dan jargon.)
Namun pasar juga membawa kejahatannya sendiri. Bukan hanya karena dia hanya memperkaya kaum kapitalis yang tak berhati namun, sebagaimana dikatakan kaum formalis -- kaum pembela kebudayaan tinggi -- pasar mendiktekan citarasa, bahkan menyeragamkannya, sehingga ia bukan lagi mendorong demokratisasi. Manusia-konsumen menjadi bulan-bulanan produk dan gaya terbaru, sehingga ia kehilangan kebebasan dan hasrat-untuk-mencipta: kebebasan-untuk-membeli hanyalah sejenis kesadaran palsu. Pasar meminggirkan pencipta sejati yang benar-benar menguarkan kegelisahan dan ketakutan manusia modern. Kemudian, budaya massa menghancurkan keseriusan disiplin yang justru diperlukan untuk menopang modernitas dan menekan eksesnya.
Kritik semacam ini justru, secara ironis, menjadi umpan balik bagi industri kebudayaan itu sendiri. Dengan kata lain, tanpa serangan yang demikian, kapitalisme tak mungkin memperbaharui diri. Tanpa kreatifitas, eksperimen, dan akhirnya penghormatan pada hak konsumen, industri kebudayaan akan jenuh, mandeg, dan akhirnya bangkrut. Namun, kita tahu, kebudayaan industri -- maaf, aku mungkin agak membingungkan engkau dengan permainan kata "kebudayaan" dan "industri" -- adalah sisi lain masyarakat demokratis. Tidak ada kemajuan tanpa lembaga pendidikan dan riset yang baik, juga kemantapan hukum dalam arti perlindungan hak warga. Jelaslah, kemajuan di bidang keilmuan dan kesenian berbanding lurus dengan pertumbuhan industri.
Salah satu aspek penting dari masyarakat sipil adalah bahwa kesenian -- yang pernah dianggap sebagai produk kebudayaan tinggi, katakanlah milik borjuasi -- bersifat publik. Museum seni rupa, misalnya, yang kerap diserang sebagai pembela Erosentrisme atau Amerikosentrisme itu misalnya, rupanya sanggup mengkhalayakkan seni rupa: misalnya, avantgardisme di suatu masa tertentu, perlahan-lahan akan menyatu dengan citarasa dan pengetahuan khalayak luas karena museum itu juga berfungsi sebagai sejenis lembaga pendidikan bagi siapa saja.
Sementara itu, sebuah museum saja, yang sering dihujat sebagai pembela pandangan tertentu (misalnya modernisme) bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan terbaru dalam filsafat dan pemikiran, sehingga ia bisa ajeg memperbarui kriteria untuk koleksi dan segenap pamerannya. Dengan sendirinya, seribu museum adalah perayaan terhadap pluralisme: penggerogotan terhadap pandangan serba tunggal dan dominan.
Bila permuseuman, akademi, kritik seni dan jaringan yang terkait dengannya sudah mantap, avantgardisme -- yang dulu sering dikecam sebagai puncak elitisme -- tak akan lagi jadi masalah. Dengan wajar ia akan menjadi tanda kemajuan itu sendiri, dan dengan cepat pula ia akan terserap ke dalam cita rasa publik. Lagipula, apa anehnya dengan pencipta yang selalu ingin "memimpin" kelompok disiplinnya dengan temuan terbaru?
Sebagaimana kaum ilmuwan dan kaum lain, kaum seniman juga berlomba-lomba melakukan pembaharuan. Dengan demikian, misalnya, kubisme berderajat sama dengan fisika kuantum: pada mulanya "tak berguna" dan tak komunikatif, karena melawan tradisi dan kepercayaan umum. Seniman dan ilmuwan pergi ke menara terpencil supaya ia tak tenggelam dalam tepuk tangan massa. Namun, pada saat yang tepat kemudian, kedua produk "elitis" itu menjadi faktor sosial yang baru. Yang tinggi (dari menara gading) itu turun ke bumi untuk menjadi yang sehari-hari, "mengubah dunia."
Sejarah seni selalu merupakan tarik menarik antara formalisme dan "kontekstualisme." Avantgardisme selalu mengandung titik jenuhnya sendiri. Setelah modernisme tinggi (high modernism), perkembangan seni bulan lagi perkembangan linier. Salah satu aspek darinya adalah penyerapan intensif kebudayaan populer. "Jika pasar menghancurkan batas antara yang atas dan yang bawah, kenapa aku tak menyertainya, bahkan mendahuluinya, dengan rela," demikianlah kira-kira kata si seniman. "Ketimbang aku mengejek selera umum, bukankah lebih baik aku mencibir diri sendiri? Bukankah lebih baik bermain-main dengan budaya populer demi memperkaya khazanahku ketimbang memusuhinya jika aku mandul dengan meninggikan kaidah estetik yang ternyata membelengguku?"
Demikianlah aku hanya mencoba memparodikan pendirian mereka yang menghasilkan, misalnya, Pop Art, Gerakan Seni Rupa Baru, Kelompok Apotik Komik (Yogyakarta), novel "realisme magis", arsitektur pascamodern, musik minimalisme, dan teater multimedia.
DEMIKIANLAH, wahai anak-anak masa depan, aku suka bermain-main di antara yang tinggi dan yang rendah. Bahasaku kali ini, misalnya, begitu serta-merta, dan mungkin sedikit banal. Aku tahu puisi tak selalu dapat digunakan untuk segala hal, juga dalam berbicara kepada kalian. Kelak, jika kalian menjadi pendukung cultural studies, kajian budaya -- sesungguhnya kajian budaya massa -- yang sekarang sedang ngetren di segala penjuru, mudah-mudahan itu bukan karena kalian terlalu banyak berkubang dengan televisi dan video game dan miskin sekali membaca buku. Mudah-mudahan. Lain kali kita bertengkar lagi.
posted by mr 10:47 PM
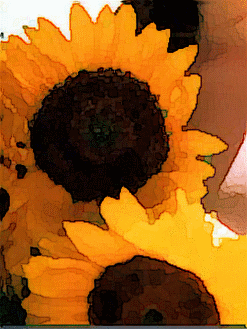
blog TOELIS, diisi oleh beberapa manusia. jika berminat untuk ikut menggunjingkan, menumpahkan, membumikan, atau mengumpatkan apa saja silakan kirim email ke anfus@frogshit.com dengan subject: ruang tulis
