| TagBoard |
arsip

Wednesday, February 27, 2008
IFJ demands reinstatement of unfairly sacked journalist in Indonesia
The International Federation of Journalists (IFJ) is outraged by the sacking and illegal treatment of an Indonesian journalist known for his campaigning for higher media standards.
According to IFJ affiliate, the Alliance of Independent Journalists (AJI), Bambang Wisudo was fired by his employer, KOMPAS Daily, on December 8 after refusing to be reassigned to Ambon, Maluku Province.
AJI reports that KOMPAS tried to budge Wisudo in order to dilute his efforts as Secretary of the KOMPAS Trade Union (PKK), where he struggled to institute changes to management policies in an attempt to lift the quality of KOMPAS’ reportage.
"It is a sad day when a journalist who has given 15 years of loyal service to a newspaper can be dismissed, unlawfully treated, and despised for his efforts to improve important media standards," IFJ President Christopher Warren said.
According to AJI, KOMPAS security personnel forcibly removed Wisudo from the KOMPAS office and detained him in a holding cell for several hours until the delivery of a dismissal letter signed by the KOMPAS editor in chief, Suryopratomo.
AJI reports that the actions of KOMPAS Daily against Wisudo are prohibited by the Indonesian Constitution and Labour Law, exposing the company to possible criminal sanctions.
"The IFJ calls for KOMPAS to immediately reinstate Wisudo and to launch a review of its management, which has shown incredible disrespect towards its employees and acted illegally on several counts," the IFJ president said.
The IFJ supports AJI in their demands for KOMPAS Daily to do the following:
· Reinstate Wisudo to his former position at PT KOMPAS Media Nusantara.
· Recognise Wisudo's role as secretary of the PKK.
· Rescind the decision to send Wisudo to Ambon, Maluku Province and abandon its continued policy of union member relocation.
· Respect the right of employees to form and elect representatives to trade unions without intimidation.
· Conduct a thorough, transparent investigation of the events listed herein and take decisive corrective action against its internal security personnel.
"The time has come for media owners to acknowledge the full right of their employees to participate in trade unions, and to cease the relentless intimidation and efforts at silencing those most active among the unions," Warren said.
For further information contact IFJ Asia-Pacific +61 2 9333 0919
The IFJ represents over 500,000 journalists in more than 115 countries
posted by wahyu.dhyatmika 6:55 PM
“Kompas Daily” fires journalist-cum-union-leader for refusing reassignment; AJI calls it a move to undermine union.
The Alliance of Independent Journalists (AJI) protests the dismissal of senior journalist Bambang Wisudo from “Kompas Daily” on 8 December 2006 and the intimidating manner in which it was done.
Bambang, who is also secretary of the Kompas Trade Union, has worked for the Jakarta-based newspaper for 15 years.
He was purportedly dismissed for refusing to be reassigned to Ambon, in the Maluku Province, 2,300km east of Jakarta.
However, AJI said that Wisudo’s reassignment was prompted by his efforts to improve the union’s reportage standards and address policies instituted by the newspaper’s management seen to be disruptive to workforce productivity and the readers.
AJI strongly condemns the atmosphere of intimidation created by the “Kompas Daily” management when the company’s security personnel forcefully removed Bambang from the office and detained him against his will for several hours in a holding cell.
Bambang was only released upon being delivered a dismissal letter signed by Editor-in-Chief Suryopra tom o.
AJI said Kompas Daily’s “intimidation, detention, and dismissal of (Bambang) are reprehensible, inhumane, and illegal.”
It continued, “The ‘Kompas Daily’ management’s efforts to restrict human rights and curtail collective efforts to improve communications are prohibited by the Constitution and labour law, and could result in criminal sanctions.”
AJI demands that “Kompas Daily” take the following actions:
- Reinstate Bambang to his former position at PT Kompas Media Nusantara.
- Recognise the workers’ right to elected representation and Bambang’s role as the union secretary.
- Rescind the decision to send Bambang to Ambon and abandon its policy of relocating union members.
- Respect the workers’ right to assemble and form trade unions without intimidation.
- Review the management’s culture of intimidation, starting with a thorough, transparent investigation of the events behind Bambang’s dismissal and a decisive, corrective action against the company’s security personnel.
Please send your support by sending your protest letters to PT KOMPAS Media Nusantara, addressed to:
Mr. Jacob Oetama, Mr. St Sularto and Mr. Suryopra tom o.
Facsimile: +62 21 548 6085, 548 3581
E-mail: kompas@kompas.com
posted by wahyu.dhyatmika 6:53 PM
Film perjuangan Bambang Wisudo melawan PHK semena-mena di harian Kompas, bisa dilihat di situs YouTube at https://www.youtube.com/watch?v=GLETBFl5srI
posted by wahyu.dhyatmika 6:49 PM
Press Release
Peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2007:
JURNALIS TOLAK AMPLOP, PERJUANGKAN UPAH LAYAK!
Jurnalis adalah buruh. Itulah kenyataannya. Sayang, hingga kini, nasib jurnalis masih belum secerah yang diharapkan. Upah jurnalis masih jauh dari kata layak. Jika dibandingkan dengan upah jurnalis Malaysia ataupun Thailand, gaji jurnalis Indonesia hanya seperempatnya. Menurut Dewan Pers, saat ini tersebar 829 media cetak, 2.000-an stasiun radio, dan 65 stasiun televisi. Namun, perusahaan media cetak yang berkualitas hanya 249 perusahaan atau 30%, sementara media elektronik yang layak bisnis cuma 10%.
Artinya, begitu mudah pemodal mendirikan perusahaan media, tapi tak memperhitungkan kelayakan kesejahteraan pekerjanya. Pengusaha media kerap berlindung di balik rendahnya tiras, iklan yang minim, dan lain-lain, untuk tidak menaikkan upah dan kesejahteraan pekerjanya. Celakanya pula, di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur tentang kelayakan modal sebuah perusahaan media bisa berdiri, termasuk berapa besar perusahaan media minimal harus mengupah pekerjanya.
Menurut survei AJI Indonesia pada 2005, masih ada media yang menggaji jurnalisnya Rp 200 ribu sebulan. Sebuah angka yang masih sangat jauh dari upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, jelas. Mutu liputan jadi asal-asalan, dan banyak jurnalis yang terjebak di dalam pusaran amplop. Padahal amplop makin mengaburkan jurnalis dari independensi dan objektivitas. AJI memang sejak awal berdiri dengan tegas menolak amplop. Solusinya, apalagi jika bukan upah layak bagi jurnalis.
Menurut survei AJI Jakarta tahun 2006, upah layak minimum jurnalis Jakarta sebesar Rp 3,1 juta. Tentu jumlah tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi inflasioner saat ini. Angka ini bukanlah angka yang muluk. Jurnalis bisa meraihnya dengan cara perjuangan bersama. Solidaritas, berorganisasi, berserikat adalah kuncinya.
Namun, perjuangan jurnalis melalui serikat pekerja, harus diakui, membutuhkan stamina yang panjang. Tak jarang terjadi manajemen menghalangi sikap kritis jurnalisnya. Tindakan anti-serikat masih kental terasa di beberapa media. Padahal hak berserikat dilindungi oleh Undang-Undang 21/2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja.
Contoh telanjang yang bisa kita lihat adalah pemecatan jurnalis Kompas, Bambang Wisudo, Desember silam. Pendepakan Wisudo yang tak lain adalah sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK), sangat kental beraroma pemberangusan aktivitas serikat pekerja (union busting). Wisudo dimutasi ke Ambon—sementara Syahnan Rangkuti (ketua PKK) dimutasi ke Padang—setelah
beberapa waktu sebelumnya PKK berhasil mendesak manajemen Kompas untuk memberikan deviden saham karyawan sebesar 20%.
Itulah. Nasib jurnalis memang begitu ironis. Jurnalis galak dan garang mengritik pedas setiap kebijakan pemerintah dan penguasa, tapi tak punya posisi tawar di hadapan manajemennya sendiri. Ibarat kata, besar di luar namun kecil di dalam perusahaannya sendiri. Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Jurnalis harus bersatu, berbareng bergerak
memperjuangkan hak-haknya.
Oleh karenanya dalam peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2007 ini, AJI Jakarta menyerukan kepada seluruh pekerja media (jurnalis, bagian iklan, percetakan, sirkulasi, keuangan, dan lain-lain) untuk bersatu mengorganisasikan diri dalam serikat pekerja. Selain itu, dalam hari kemenangan kaum buruh sedunia ini, AJI Jakarta juga menuntut:
1. Perusahaan media untuk memberikan upah layak bagi jurnalis atau seluruh pekerjanya.
2. Perusahaan media untuk memberikan hak berserikat kepada pekerjanya.
3. Hentikan pemberangusan serikat pekerja di perusahaan media.
Dengan upah yang layak, integritas jurnalis makin terbangun. Mutu media pun makin terasah.
Jurnalis Juga Buruh!
Persatuan bagi Pekerja Media!
Jakarta, 30 Mei 2007
Winuranto Adhi Jajang Jamaludin
Koordinator Divisi Serikat Pekerja Ketua AJI Jakarta
posted by wahyu.dhyatmika 6:44 PM
AJI Terbitkan Panduan Hukum untuk Jurnalis
Rabu, 28 Desember 2005 | 11:05 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Aliansi Jurnalis Independent Jakarta, Rabu (28/12) pagi, meluncurkan buku "Panduan Hukum untuk Jurnalis". Buku ini diharapkan bisa memberi panduan bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya sehari-hari.
Buku ini disusun, kata ketua AJI Jakarta Ulin Niam Yusron, dari keprihatinan kami atas banyaknya gugatan hukum terhadap pers. "Semoga setelah membaca buku ini, wartawan tidak mudah disomasi," katanya.
Buku ini disusun sejak 6 bulan lalu dan disarikan dari sejumlah diskusi intensif yang melibatkan Dewan Pers, wartawan, dan pengacara. Polisi, jaksa, dan hakim juga ikut memberi masukan," kata Ulin
Peluncuran buku hari ini ditandai dengan diskusi tentang kriminalitas dan kekerasan pada jurnalis berbicara dalam diskusi ini, ketua Dewan Pers Ichlasul Amal, Advokat Luhut Pangaribuan, dan penulis buku ini, Margiono dari AJI Jakarta. | wahyu dhyatmika
posted by wahyu.dhyatmika 6:43 PM
Thursday, June 07, 2007
Regulating Cyberspace, A Utopia?
SOUTH Korean Broadcasting Commission is busy fighting an intense row at the moment. The news is; their archenemy is not the big commercial television tycoons as it used to be. Today, they have to face angry responds from their own supposed to be colleagues-- South Korean Ministry of Information and Communication.
Their row, which was erupted in the beginning of April this year, is regarding Web TV regulation. The commission want to start a pilot project of Internet protocol based television in order to develop a regulatory framework for the new service. However, the plan was strongly opposed by Ministry of Communication, which reportedly said that IP-based TV is just an extension of telecommunications. “It would be a stretch to say that video content on the Internet should be considered as broadcasting right now,” said a Communication Ministry official, quoted by a BBC report.
Unsurprisingly, the two regulators had similar conflict last year, when the broadcasting regulator claimed jurisdictions over mobile phone-based video-on-demand products. A claim that sparked heated debate; what are the boundaries between broadcasting and telecommunications? Some even dare to take it further; is the boundaries still exist?
The South Korean case is not the only ongoing debate today over cyberspace regulations. Blogging, an increasingly popular habit amongst ‘netizens’ is also creating real problem outside the cyberspace borders.
Ellen Simonetti’s story represents the debate accurately. She was a flight attendant for Delta Airlines in Texas. Not anymore. Last fall, her company sacked her for posting an image of herself with Delta’s uniform in her own blog. Simonetti immediately brought the case to U.S. Equal Employment Opportunity Commission and is still fighting to get her job back. She said if she'd known what the repercussions would be, she would never have posted the photos.
Similar case of companies firing their blogger-employee over so called ‘sensitive information dissemination’ also happened in Microsoft, Google and many more. All of that triggered the long unresolved debate; how can we regulate cyberspace without hampering creativity and free speech, which are two of the strongest driving forces behind Internet development?
The Saga Begins
HOWEVER, the biggest irony probably is the fact that ten years ago nobody would consider regulating cyberspace is a serious idea. Indeed, Internet has change so fast; even the most progressive law makers find it difficult to keep up with the pace.
October last year, the US House of Representatives approved an anti spy Act to protect Internet users from software that deliberately designed to take control of their computers. These ‘spyware’ has the ability to hide in PCs hard drive and secretly monitor its activity. They also can modify web browser’s homepage and dismantle its anti-virus software without proper authorization.
Sounds like a significant tool to protect consumers’ right, isn’t it? Read this; last February, no more than four months after the house approved the Spy Act (even tough the Senate never voted for it), the same legislative body now has considered revising it.
Several lawmakers are believed to think that the Act was too broad and has outlaw ‘cookies’, tiny tags used by webmasters to keep track their website effectiveness or by online marketing firms to monitor its advertising program. In the US, online marketing and Internet behaviour analysis has become a huge business. Some concern that making those practises illegal could stall Internet’s rapid transformations into a fully worldwide profit-making medium.
However, keep in mind, that within four months, proliferation of harmful ‘spyware’ has also rose and need tougher measures. Thus, its like being in a cul-de-sac situation, anything you do seems like never going to be enough.
***
IN its early development, many people refer to the web as the new free world, where there’s no restriction whatsoever of things you can post and download. But nowadays, things have certainly changes dramatically.
People use Internet to seek any kind of information, from cooking recipes and song lyrics to pop-stars porn videos. Reciprocally, people put up all kind of things to the web, from Al-Qaeda execution clips to a diary of a newborn baby. As the result, the Internet attracts more and more people.
In one interview, the website usability Guru, Jakob Nielsen, explained that the possibility of Internet transforming into a fully open market where people trade goods and information is just a click away. “We will need micropayments and other forms of payment solutions, but once we have that, you should be able to find anything you want on the Web. Currently, much of the best information is still locked up because it doesn't pay to just give it away,” he said.
Slowly but surely, people start making money out of the web. It’s inevitable. And once Internet becomes a market, firms begin to take action to protect its profitability. One of their actions will be encouraging lawmakers to introduce more and more regulation to netters.
Nevertheless, the question remains; will heavy regulations prevent web entrepreneur from blossoming? Will it be the end of the free world slash free Internet era if companies eventually find ways to restrict its employee from blogging about their jobs? Will Internet be better of without any kind of regulation?
Ethical Dilemma
OF course not all regulation is bad for Internet development. Limiting ‘spyware’ is a good thing. So do keeping business secrets and intellectual properties safe from the reach of potential competitors. Plagiarism, libel, spreading of violence and religion sensitive materials; all sort of criminal offence in the web should be addressed with proper regulation.
However, above all that, netters have to decide; who will have the privilege to make the boundaries of what is lawful and not? Who will have the power to define ‘Internet offence’?
The proliferation of websites, chat rooms, mailing list and all sort of Internet-based gadgets in recent times is a thing no one has ever witnessed before. Text, images, clips, sounds, songs, and movies can multiply and spread across the globe in seconds. Its plausible then to think that all terms has to be re-defined in the online world.
For instance, what is libel in the web? It is of course libel to spread bogus rumours about a firm performance in a business chat forums that subsequently can affect its value in the stock exchange. But is it libel to publish a personal account about your personal feeling at work in your personal blog? Is it plagiarism to link your website to another richer-content website, in order to help your site’s visitors to get a fuller view of an issue? Is it plagiarism to create a better website for a particular service because the original website just don’t get it? (The case of David Somerville who copy and fix British Odeon cinema chain and end up getting more hits than the real Odeon website).
Those questions are only a glimpse of what Internet regulator has to face up with. There is still a long list of issues to be discussed; can lawmakers grasp the dynamic of Internet, the open source and decentralised linking web’s philosophy, all the energy that boost Internet development phenomenally in recent years? Say, optimistically-- they can. Then, can those web-based principles applied outside cyber border?
The David Shayler case is a good example. Back in 1997, the former MI5 agent threatened to publish detail of British intelligent agency’s alleged plan to kill Libyan leader, Colonel Moammar Ghadaffi in a website he created in exile. Shayler himself was wanted in Britain for breaching Official Secrets Act after revealing details of his MI5 organization in the ‘Mail on Sunday’ newspaper. Can he be punished for things he done in the web? Was the injunction effective for a website content outside British jurisdiction?
Again, those are just a glimpse of all the debate about Internet law and ethical issues.
Indeed, inside Internet world, everything must be seen from a new perspective. The very nature of the medium that allowed websites to intertwined and linked to create an array of rich information useful for all-- has to be taken into consideration. Netters and lawmakers have to find a common ground, to balance the need for regulated cyberspace that also still gives breathes for creativity and personal freedom. They don’t have much time left, since that common ground has to be found now, before Internet grows even greater than it has today.
The Next Big Thing
In ten years time, Internet will develop beyond imagination. It has come a long way since its first creation as war software developed by US military. Broadband’s wider penetration all over the world will change how website is used and designed. People will use Internet, not only for e-mail, getting flight reservation or finding resources in the web, but for all sorts of things. Nowadays, people increasingly use it as a news outlet.
“I think that they (websites--) might get to really replace newspapers. One, you can read them on a flat screen instead of hold at your breakfast table, instead of going to your office and read it on a traditional monitor, that's not really good enough to replace the printed newspaper. But I think ten years from now, we might use the Web much more for news,” said Jakob Nielsen in an interview with CNN.
The launch of PC Tablets by Microsoft two years ago and Mini Mac by Apple just a couple of months ago, confirm Nielsen’s prediction. RSS system makes it even easier to keep track of all the latest news through a self-filtered news feeder. Many leading newspapers in America and UK now have their own viewpapers available online. Mobile 3G wave and flat screen television will help pave the way to the surfacing of users friendly-multiple platform news agencies.
Press Association in UK is one leading example of how a news organization prepared itself for the next big thing; integration of all media outlet based on news-on-demand scheme. And that is just the beginning. (*)
posted by wahyu.dhyatmika 1:34 PM
Korupsi Di Sekitar Kita
Orang melakukan korupsi, pertama-tama bukan karena dia mendapat kesempatan dan tahu bagaimana melakukan korupsi, tapi karena tahu lingkungan di sekitarnya juga korup.
PEMERINTAH daerah di Indonesia pasca reformasi 1998 adalah lembaga eksekutif yang super. Setelah selama lebih dari tiga dekade hanya berperan sebagai pion-pion kepanjangan tangan rejim Orde Baru yang sentralistis, sekarang mereka memiliki wewenang –dan kesempatan-- besar untuk menentukan baik buruknya pelayanan publik yang dinikmati warga negara. Aparat pemerintah daerah berada di garda terdepan pemerintahan, sebab merekalah yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Arsitek otonomi daerah, Profesor Ryaas Rasyid, pernah mengatakan bahwa salahsatu dasar pemikiran di balik Undang Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 adalah usaha untuk mendekatkan rakyat kepada pemerintahnya. Jika persoalan-persoalan pembangunan bisa diselesaikan di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi, kata mantan Menteri Negara Urusan Otonomi Daerah ini, maka roda pemerintahan secara nasional bisa berjalan lebih efektif. Selain itu, dengan pengelolaan secara swadaya di daerah, potensi keunggulan daerah pun bisa dimanfaatkan secara optimal. Triliunan rupiah keuntungan dari hasil pengolahan sumber-sumber daya alam tidak lagi dilarikan ke pusat, ke Ibukota Jakarta, melainkan sebagian besar bisa diputar di daerah, untuk menggerakkan roda ekonomi yang pada akhirnya diharapkan bisa mengangkat taraf kesejahteraan warga negara pembayar pajak.
Oleh sebab itu, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, penegakan prinsip pengelolaan pemerintahan yang bersih dan efektif (clean and good governance) sudah seyogyanya dilakukan pertama-tama dan terutama di tingkat pemerintahan daerah. Jika kinerja pemerintah daerah membaik dan partisipasi rakyat meningkat sehingga akuntabilitas pejabat publik pun terjaga, maka dengan sendirinya peluang mencapai kesejahteraan yang adil dan merata bagi warga pun menjadi lebih besar.
Karena itu, sungguh menyedihkan menyaksikan bagaimana otonomi daerah selama delapan tahun pertama penerapannya justru membawa lebih banyak kabar buruk ketimbang kabar baik. Banyak orang kini dengan sinis menilai kebijakan otonomi daerah hanya berhasil mendesentralisasi korupsi, melahirkan raja-raja baru di berbagai kabupaten dan kota, serta melanggengkan praktek pemerintahan yang buruk, tidak transparan dan menyengsarakan.
Kecenderungan ini diperparah oleh bersemangatnya elite-elite daerah –dengan dukungan patron mereka di Jakarta—memekarkan kabupaten, kota dan provinsi, dan menyulap daerah hasil pemekaran itu menjadi kapling-kapling baru untuk memperoleh kekuasaan ekonomi dan politik bagi kelompoknya.
Tengok apa yang terjadi di dua ujung kepulauan Nusantara, Aceh dan Papua. Salahsatu penyebab utama sebagian rakyat di dua provinsi itu tidak puas menjadi bagian dari Indonesia dan menuntut merdeka adalah parahnya korupsi yang dilakukan pejabat daerah di sana. Karena Bupati dan Gubernur dinilai warga sebagai representasi Jakarta, maka kepala daerah yang korup --mau tidak mau—juga menjadi cermin birokrasi pemerintah pusat yang tidak becus, mementingkan kepentingan segelintir orang dan tidak menyejahterakan rakyat.
Mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, menyunat anggaran daerahnya untuk berbagai proyek yang tidak jelas ujung pangkalnya. Di tengah masa jabatannya, pada 2002, dia menjadi tersangka untuk tak kurang dari 11 kasus dugaan korupsi, termasuk kasus pembelian mesin pembangkit listrik tenaga solar senilai Rp 30 miliar, penggelembungan harga helikopter Mi-2 dari Rusia, pembelian mesin cetak dan mobil dinas. Kasus pengadaan heli bekas itu akhirnya menyeret Puteh ke balik terali besi. Pada April 2005, dia divonis 10 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Di ujung timur Nusantara, mantan Bupati Jayawijaya, Papua, David Agustein Hubi, memanipulasi anggaran daerah untuk membiayai pembelian dua pesawat Fokker 27 seri 600 senilai Rp 17,2 miliar. Tidak hanya itu, Hubby juga menggunakan anggaran daerahnya yang terbatas untuk menyewa pesawat Antonov senilai Rp 3,9 miliar. Sampai masa jabatannya berakhir, rakyat Jayawijaya tidak pernah melihat wujud dua pesawat Fokker maupun Antonov itu. Agustus 2006 lalu, Pengadilan Negeri Wamena menjatuhkan vonis lima tahun penjara untuk David Hubi.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), sebuah lembaga non-pemerintah yang secara rutin memantau perencanaan dan penggunaan anggaran daerah di seluruh Indonesia, dua tahun lalu merilis catatan merisaukan ini: kerugian negara akibat korupsi daerah sudah mencapai Rp 443 miliar. Yang lebih mengejutkan, angka kerugian itu hanya akibat korupsi anggaran daerah selama periode 1999-2004 lalu. Itu pun baru berdasarkan data dari 45 kabupaten dan kota. Belum termasuk korupsi yang tidak dilaporkan masyarakat dan tidak menjadi konsumsi publik melalui liputan media. Dashyat.
Gejala macam ini jelas adalah kemunduran yang berbahaya. Selain menjauhkan rakyat dari target pembangunan yang seharusnya menyejahterakan mereka, kondisi macam ini berpotensi menjadi pintu masuk untuk kembalinya desentralisasi dan pemusatan kembali kewenangan pengelolaan pembangunan dan keuangan ke tangan pusat. Kemungkinan ini sudah mulai tercium dari bagaimana seringnya pejabat pemerintah pusat mengeluh soal sulitnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan nasional, dan makin seringnya pakar dan pengamat politik ekonomi di Jakarta dengan blak-blakan memberi label ‘otonomi kebablasan’ pada kebijakan otonomi daerah 1999.
Sebagian kekhawatiran ini bahkan sudah terbukti dengan revisi UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1999-2004 merilis peraturan baru ini pada minggu-minggu terakhir kekuasaan mereka pada Oktober 2004. Pada undang-undang yang sampai kini masih kontroversial ini, sebagian kewenangan pemerintah daerah diambil lagi oleh pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negeri.
Karena itu, sebenarnya tidak ada pilihan lagi, kecuali memenuhi harapan masyarakat yang terlanjur membumbung tinggi kepada otonomi. Desentralisasi dan dekonsentrasi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah di kabupaten dan kota harus berhasil membawa perubahan berarti bagi kesejahteraan rakyat. Tidak bisa tidak.
Nah, salahsatu indikator terpenting keberhasilan itu adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif di daerah. Seharusnya sudah tidak ada lagi toleransi untuk pemborosan keuangan negara dan korupsi. Masa bulan madu otonomi daerah –dimana pejabat daerah berlomba-lomba mengutil anggaran untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, tanpa upaya pengawasan warga yang memadai—sudah saatnya berakhir. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melunasi janji manis otonomi daerah.
Tak bisa dipungkiri, korupsi adalah hambatan terbesar dalam upaya realisasi target-target pembangunan di daerah. Bocornya anggaran daerah --entah lewat penggelembungan besaran anggaran, bagi-bagi komisi proyek sampai penyalahgunaan pos anggaran—menyunat kemampuan pemerintah daerah melaksanakan program pembangunan yang menyentuh kehidupan orang banyak. Jika ini dibenahi, niscaya persoalan terbesar buruknya kinerja pemerintah daerah, akan teratasi. Soal-soal lain –seperti peningkatan kapasitas pemerintah lokal agar ketidakmampuan membuat prioritas program dan ketakbecusan pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif tidak lagi membuat orang mengelus dada-- bisa menyusul belakangan. Sedemikian besarnya efek pembersihan korupsi di daerah, banyak orang meramalkan roda pembangunan bisa bekerja dua kali lipat lebih efektif, jika kanker ini berhasil dipotong dan dibuang dari sistem pemerintahan daerah kita.
Ini soal lain tapi masih erat berkaitan: sejak lima tahun terakhir, sudah tak terhitung lagi banyaknya berita soal korupsi anggaran daerah menjadi konsumsi publik. Sebuah survei sederhana bisa mengungkap rendahnya kepercayaan publik kepada pejabat pemerintah di daerah. Temui satu warga di pinggir jalan dan coba tanyakan apakah dia yakin kepala daerah di wilayahnya tidak melakukan korupsi. Hampir pasti sebagian besar dari mereka akan berpikir sejenak sebelum menjawab ya atau tidak.
Jika kenyataannya separah ini, pasti ada yang harus diperbaiki dalam gerakan besar pemberantasan korupsi di negeri ini. Mengapa setelah sekian lama isu anti korupsi bergulir, kepercayaan publik masih begitu rendah? Mengapa publik begitu yakin bahwa kasus-kasus korupsi yang terungkap di media hanya puncak dari sebuah gunung es raksasa?
Diakui atau tidak, model pemberitaan isu korupsi di media kita berkontribusi pada terciptanya kondisi ini. Selama ini, wartawan masih menjadi aktor figuran dalam gerakan pemberantasan korupsi. Sebagian besar koran, majalah, radio dan televisi –baik di Jakarta maupun di daerah-- baru memberitakan korupsi ketika polisi atau jaksa menyelidiki suatu kasus. Wartawan baru menulis soal pejabat korup ketika yang bersangkutan diperiksa polisi dan jaksa.
Akibatnya agenda pemberantasan korupsi pun disetir oleh para penegak hukum ini. Padahal –seperti sudah ditunjukkan beberapa survei Transparency International Indonesia-- rakyat yakin benar bahwa polisi, jaksa dan hakim adalah bagian dari persoalan korupsi di Indonesia. Tidak heran jika sampai hari ini, publik masih menyimpan keraguan soal serius tidaknya pemberantasan korupsi di negeri ini.
Jawaban untuk persoalan pelik ini adalah jurnalisme investigasi. Sudah saatnya wartawan mengambil peran yang lebih berarti dalam gerakan pemberantasan korupsi dengan menjadi ujung tombak membongkar kasus-kasus korupsi yang –entah disengaja atau tidak—luput dari perhatian aparat penegak hukum. Hanya dengan cara itu, wartawan bisa menjalankan kewajibannya kepada publik.
***
INI pertanyaan yang paling sering berkecamuk di benak kita: mengapa para pejabat publik melakukan korupsi? Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat sejumlah jawaban atas pertanyaan besar itu.
Pertama, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini tidak transparan. Akibatnya apa yang dibahas dan kemudian diputuskan dalam anggaran daerah tidak pernah diketahui masyarakat, yang jelas-jelas merupakan pemangku kepentingan utama anggaran itu. Tidak hanya itu, banyak warga juga tidak tahu kapan APBD mulai dibahas, ditetapkan dan kemudian dipertanggungjawabkan.
Kedua, tidak ada pengawasan. Karena sifatnya yang tertutup, jangan heran jika sejak perencanaan, penetapan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban APBD pun luput dari perhatian masyarakat. Hanya beberapa daerah yang beruntung memiliki sejumlah lembaga non-pemerintah maupun akademisi yang setia memantau seluruh proses itu. Itupun jumlahnya terbatas dan kadang tidak didukung infrastruktur kelembagaan yang memadai.
Ketiga, kekuasaan berlebihan di tangan pejabat pemerintahan daerah, baik di pemerintah maupun parlemen. Sejak era otonomi daerah, para pejabat daerah ini memiliki hak mengelola daerah sesuai selera mereka. Akibatnya, banyak pos belanja APBD diselewengkan untuk kepentingan kelompok yang dekat dengan mereka, dan terutama, partai politik.
Keempat, tidak ada partisipasi publik. Nyaris di semua daerah, warga seakan tidak punya suara menentukan untuk apa anggaran dibelanjakan dan berapa besar. Ini kesalahkaprahan terbesar dalam sistem demokrasi perwakilan di negeri ini. Partisipasi publik seakan dinafikan begitu kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Rakyat hanya menjadi obyek pembangunan, yang suaranya baru dianggap penting saat kampanye pemilu.
Kelima, akuntabilitas pemerintah daerah dan parlemen daerah yang rendah. Jika tekun menelisik satu demi satu laporan pertanggungjawaban APBD di kabupaten, kota maupun provinsi, akan tampak jelas kalau sebagian besar laporan itu tidak memenuhi standar. Anehnya, laporan yang compang-camping dan tidak jelas indikator keberhasilannya seperti itu, seringkali lolos dan diterima begitu saja oleh parlemen daerah. Penyebabnya sederhana: ada kongkalikong antara badan legislatif dan pejabat eksekutif di daerah. Tak jarang mereka berkomplot bersama-sama menyunat APBD.
***
Seperti sudah banyak diulas sejumlah pengamat politik, sistem pemilihan pejabat publik –baik kandidat kepala daerah maupun calon legislator-- di negeri ini juga menyumbang pada sulitnya membersihkan pemerintahan daerah dari tikus-tikus berdasi ini. Meski tentu tidak semua, sudah jadi rahasia umum, bahwa menjadi calon legislator dan kepala daerah dari partai politik, seseorang harus mengeluarkan fulus sampai jutaan rupiah. Labelnya beragam: mulai uang sumbangan partai politik, kontribusi kampanye sampai uang mahar.
Di luar fulus yang masuk ke kas partai itu, seorang calon pejabat publik yang ingin menang di pemilihan umum tentu harus merogoh kocek untuk membiayai kampanye, membeli alat peraga –poster, spanduk dan stiker--, memasang iklan di media massa sampai membayar honor saksi di tempat-tempat pemungutan suara. Jumlahnya bisa mencapai ratusan juta rupiah.
Setelah terpilih, keharusan memberikan setoran kanan kiri ini belum berakhir. Hampir semua partai politik mengharuskan kadernya yang menjadi pejabat publik menyisihkan gaji bulanannya untuk kas partai.
Akibatnya mudah diduga. Pejabat publik yang “ditodong” sebegitu rupa mau tidak mau harus putar otak mencari duit tambahan untuk menutup kebutuhan tak tersangka tak terduga ini. Tak sedikit yang tergelincir menjadi koruptor. Karena dilakukan untuk kebutuhan partai, para pengurus partai pun merasa wajib melindungi kadernya dari incaran hukum. Jadilah korupsi berjemaah.
Gerakan massal menghadang upaya pemberantasan korupsi jelas sekali tampak dalam kontroversi Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000. Peraturan yang dirilis di era Presiden Abdurahman Wahid itu dinilai mengebiri sejumlah hak istimewa anggota parlemen daerah dalam penggunaan anggaran daerah. Misalnya saja, beleid itu mengatur agar dalam menyusun APBD, para anggota DPRD dan pejabat pemerintah daerah memperhatikan asas kepatutan antara anggaran pembangunan untuk publik dan anggaran kesejahteraan untuk anggota parlemen daerah. Asas kepatutan yang dimaksud adalah kejelasan penggunaan dari setiap rupiah dana APBD. Bersenjatakan peraturan itu, polisi dan jaksa menyeret ratusan anggota DPRD ke pengadilan dengan tuduhan korupsi.
Reaksinya bisa ditebak. Para anggota Dewan yang terhormat berontak. Mereka mengajukan uji materiil atas aturan itu ke Mahkamah Agung. Para wakil rakyat menilai peraturan pemerintah itu melanggar undang-undang alias aturan yang lebih tinggi.
Pada 9 September 2002, Mahkamah Agung mengabulkan uji materiil tersebut dan menyatakan peraturan itu tidak berlaku lagi. Tidak cukup, asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia dan Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia mendesak Komisi Hukum DPR Republik Indonesia mempertegas keputusan MA itu. Gayung bersambut. Komisi Hukum mencecar Jaksa Agung yang dinilai mengabaikan keputusan mahkamah itu. Tidak berhenti sampai di situ, para wakil rakyat di Senayan juga meminta MA menerbitkan surat edaran yang meminta semua hakim di seantero negeri menolak mengadili perkara yang menggunakan peraturan itu sebagai dasar dakwaan jaksa.
Pada November 2006, pemerintah merilis peraturan baru. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan DPRD itu justru memicu kontroversi baru. Dalam aturan itu, jumlah penghasilan dan tunjangan para anggota dewan di daerah dinaikkan secara dramatis, plus dirapel untuk tahun anggaran 2006. Kebijakan model begini tentu memicu kemarahan banyak orang. Setelah dikritik demikian pedas, pemerintah akhirnya merevisi aturan itu, meski dampaknya pada kas daerah sudah telanjur fatal. Tak kurang dari Rp 1,3 triliun harus disediakan negara untuk membayar tambahan dana komunikasi intensif dan operasional 1.500 anggota parlemen daerah se-Indonesia.
Meski, para legislator di daerah diberi waktu sampai 2009 untuk mengembalikan duit rapelan mereka, tidak ada sanksi pidana bagi mereka yang gagal mengembalikan. Kasus ini makin jelas menunjukkan kuatnya lobi politik para politisi daerah untuk mengamankan kepentingan finansial mereka. (*)
posted by wahyu.dhyatmika 1:27 PM
Sunday, August 17, 2003
Like Mother, Like House
Anda tentu bisa menggambarkan tiap detail rumah yang Anda tempati saat masih kecil. Karena bagi anak kecil, rumah adalah tempat bermainnya pertama yang ia kenal. Bagi seorang pekerja, rumah lebih bermakna sebagai tempat merenggangkan otot. Sedangkan bagi ibu rumah tangga ?
Seorang ibu rumah tangga di Kemang menginterpretasikan rumah betul-betul sebagai tempat tinggal. Dengan seorang putri berusia empat tahun dan suami pengusaha kafe, konsep minimalis, bersih, dan modern menjadi pilihan sebagai tempat untuk menghabiskan waktunya. "Nyaman karena berkesan lebih luas, praktis karena mudah dalam perawatan serta tidak membutuhkan banyak pernak-pernik dekorasi," kata pemilik rumah.
Saya membayangkan, masa kecil gadis kecil anak pemilik rumah ini. Gadis kecil yang kadang melongok ke luar di waktu malam. Ia akan tampak seperti putri di sebuah kastil biru yang tengah menunggu pengagum. Kastil yang mengambang di atas cahaya karena sorot lampu yang mengarah ke atas. Tidak seperti dalam dongeng, putri itu menikmati kastil yang sebenarnya tidaklah terlalu luas, karena memang Kerajaan Kemang nan padat tidak mengizinkannya. Luas bangunan boks dua lantai lurus dari bawah ke atas membuat bangunan tiga lantai itu tampak longgar.
Kala gadis kecil itu pulang mengikuti ibunya shoping, ia akan disambut kanopi alumnium yang berada tepat di atas entrance dan tangga masuk. Jika ia sempat mendongak, mungkin merengek ke ibunya, grill kayu pada sisi atas dan jendela kanopi flat beton datar seakan tersenyum mengingatkannya dan seperti berbisik berkata," Jangan nakal." Tegas namun lembut.
Lalu gadis kecil itu berlari menuju kolam renang, duduk di pinggir kolam dan mencelupkan dua kakinya. Tatapnya lurus menembus kaca menatap ibunya yang duduk di ruang dalam. Kolam renang itu bukan sisi luar, tapi wilayah dalam yang merupakan bagian dari pemisahan publik dan privat.
Ibunya mungkin akan segera mengingatkannya agar tidak berlama-lama bermain air, dan bisa-bisa tercebur kuyub. Sebelum suara keras terlepas, panil-panil kayu pada dinding mengingatkannya untuk tetap hangat dan bersahabat. Panil-panil itu, seperti tak terelakkan, membuat rumah modern kontemporer berkesan lebih lunak sebagai penyeimbang ketegasan aluminium yang seakan ditebar di berbagai sudut.
Saya membayangkan ibu itu tidak jadi marah, ia lebih suka menggamit gadis kecilnya dan mengajaknya ke dapur. Ruang itu menjadi tempat bernegosiasi untuk tidak saling cemberut. Mereka bisa melihat senyum yang terpantul dari perlengkapan masak, meja dapur, cabinet, dinding meja hingga kursi-kursi yang semuanya terbuat dari stainles atau metal silver.
Jangan membayangkan logam-logam itu membuat suasana kaku. Karena permainan lampu dengan tungsen yang kreatif membuatnya terasa hangat, ramah, dan mengundang. Dari tempat ini pula mereka bisa menangkap tubuh sang ayah yang baru saja pulang. Dapur itu tampak terbuka ke ruang makan dan ruang duduk. Sehingga lambaian ayah gadis kecil itu dengan mudah dipindai mata kecilnya.
Seusai memasak cemilan usai, gadis kecil itu menggamit ibunya ke ruang baca. Ruang yang jelas terpisah dari ruang kerja ayahnya. Tak seperti ruang lainnya, dinding krem lembut hangat menyiratkan bahwa inilah tempat kerja perempuan. Si gadis kecil segera duduk di kursi berbalut velvet halus. Ia akan tampak anggun di antara coklat tanah dan merah marun itu, sementara ibunya mengambilkan satu buku cerita. Dan saya masih membayangkan, ia membacakan buku "Totto-chan". Buku yang membuat saya membayangkan "gadis kecil di jendela" itu.
anggoro gunawan
Tulisan ini interpretasi dari sebuah tulisan berjudul Cozy House for Modern Woman, hal 132, Majalah A+ edisi April - Mei.
posted by ang 10:30 PM
Wednesday, August 13, 2003
Pemenang Lomba Menulis Surat ke Presiden
Kategori Kelas I-III SD dalam Rangka Hari Anak 2003.
Dewan Juri: Seto
Kepada Yang Terhormat
Presiden Republik Indonesia Megawati
Di Istana
Assalaamualaikum.
Ibu Mega, apa kabar? Aku harap ibu baik-baik seperti aku saat ini. Ibu, di kelas badanku paling tinggi. Cita-citaku juga tinggi. Aku mau jadi presiden. Tapi baik. Presiden yang pintar, bisa buat komputer sendiri. Yang tegas sekali. Bisa bicara 10 bahasa. Presiden yang dicintai orang-orang. Kalau meninggal masuk surga
Ibu sayang,
Bunda pernah cerita tentang Umar sahabat Nabi Muhammad. Dia itu pemimpin.Umar suka jalan-jalan ke tempat yang banyak orang miskinnya. Tapi orang-orang tidak tahu kalau itu Umar. Soalnya Umar menyamar. Umar juga tidak bawa pengawal. Umar jadi tahu kalau ada orang yang kesusahan di negeri dia. Bisa cepat menolong. Kalau jadi presiden, aku juga mau seperti Umar. Tapi masih lama sekali. Harus sudah tua dan kalau dipilih orang. Jadi aku mengirim surat ini mau mengajak ibu menyamar. Malam-malam kita bisa pergi ke tempat yang banyak orang miskinnya. Pakai baju robek dan jelek. Muka dibuat kotor. Kita dengar kesusahan rakyat.Terus kita tolong. Tapi ibu jangan bawa pengawal. Jangan bilang-bilang. Kita tidak usah pergijauh-jauh. Di dekat rumahku juga banyak anak jalanan. Mereka mengamen mengemis. Tidak ada bapak ibunya. Terus banyak orang jahat minta duit dari anak-anak kecil. Kasihan. Ibu Presiden, kalau mau, ibu balas surat aku ya. Jangan ketahuan pengawal nanti ibu tidak boleh pergi. Aku yang jaga supaya ibu tidak diganggu orang. Ibu jangan takut. Presiden kan punya baju tidak mempan peluru. Ada kan seperti di filem? Pakai saja. Ibu juga bisa kurus kalau jalan kaki terus. Tapi tidak apa. Sehat.
Jadi ibu bisa kenal orang-orang miskin di negara Indonesia. Bisa tahu sendiri tidak usah tunggu laporan karena sering ada korupsi. Sudah dulu ya. Ibu jangan marah ya. Kalau tidak senang aku jangan
dipenjara ya. Terimakasih.
Dari
Abdurahman Faiz
Kelas II SDN 02 Cipayung Jakarta Timur
posted by ang 9:31 PM
Tuesday, June 24, 2003
Remy Sylado: Saya Pilih Tema yang Tidak Digarap Orang Lain
Banyak nasib baik menghampiri Remy Sylado bulan-bulan terakhir ini. Novelnya, Kerudung Merah Kirmizi menyabet Hadiah Khatulistiwa 2002. Novelnya yang lain, Ca Bau Kan telah enam kali naik cetak, difilmkan, lalu film ini masuk dalam unggulan 45 film terbaik Piala Oscar 2003 untuk kategori film luar negeri.
Sejak muda, lelaki bernama asli Yapi Tambayong —nama Remy Sylado adalah ingatan pada keberaniannya mencium perempuan untuk pertama kali pada tanggal 23 bulan 7 tahun ‘61 —ini memang selalu menyedot perhatian. Ia memelopori gerakan puisi mbeling pada 1970-an lewat Aktuil —majalah yang jadi barometer perkembangan musik Indonesia waktu itu, menggelar pengadilan puisi di Bandung, dan mementaskan pertunjukan yang bikin geger, seperti ‘Jesus Christ Super Star’. Aktivitasnya ketika itu adalah wujud perlawanannya terhadap kemapanan, termasuk pada para "penyair resmi".
Di usianya yang sudah 57 tahun, penulis Parijs van Java — novel yang beberapa waktu lalu diturunkan sebagai cerita bersambung di Koran Tempo — ini tetap sibuk. Pada 11 Januari lalu, ia bersama Oka Rusmini —penulis novel Tarian Bumi, diundang menghadiri Festival Winternachten di Belanda.
Di tengah kesibukannya me nulis —antara lain Sam Po Kong dengan 30 buku referensi, melukis, dan bepergian ke berbagai kota untuk riset dan berbicara dalam pelbagai forum termasuk ceramah teologi untuk para pendeta, Remy menerima Arif Firmansyah dari Koran Tempo untuk wawancara. Berikut petikannya:
***
TANYA (T) : Apa yang Anda lakukan dalam festival itu?
JAWAB (J) : Saya diminta berbicara tentang CaBauKan karena mereka tertarik dengan latar belakang masa kolonial Belanda. Festival itu berkepentingan melihat sikap orang Indonesia terhadap kolonialisme Belanda. Saya kan tidak melihat Belanda hitam putih. Apalagi dalam Parijs Van Java yang lebih kuat setting Belandanya. Saya melihat sebagai manusia dan bukan sebagai bangsa. Cuma saya hanya diminta berbicara tentang Ca BauKan . Apalagi filmnya masuk sebagai satusatunya film Asia di Festival Film Cannes.
(T) : Selama ini dari mana Anda mendapatkan ide penulisan?
(J) : Begini, saya selalu melihat bahwa menulis adalah sebuah pekerjaan.Dari situ saya kemudian tergerak untuk melakukan proses penulisan. Dengan begitu berarti saya punya kewajiban untuk memperoleh nafkah. Soalnya kemudian menulis kreatif atau menulis yang bukan kreatif, itu dulu. Kalau untuk penulisan kreatif saya selalu melihat peta apakah orang menulis bidang itu atau tidak.
Misalnya, melakukan riset terhadap data yang ada di masa silam tentang tamadun kita di masa lalu. Masalah itu menarik bagi saya karena banyak orang tidak mengenal sejarah masa silam. Bagaimana pertemuan bangsa kita dengan bangsa luar seperti Belanda, Inggris, Cina, dan lain lain. Cerita itu sangat menarik kalau direkakan ke masa silam seperti cerita Parijs van Java yang dimuat Koran Tempo .Selama ini kita melihat orang Belanda secara hitam putih, yakni penjajah. Kita jarang melihat ada di antara mereka yang memikirkan kemajuan Indonesia juga.
(T) : Bagaimana Anda melakukan riset untuk novel-novel Anda?
(J) : Tentu saya butuhkan riset tentang kondisi masa itu.Setiap akan menulis saya selalu mengumpulkan bahan. Nah, saat menulis kadang cerita berkembang karena ada data baru yang masuk. Data yang baru saya dapatkan biasanya saya selipkan dalam alur cerita.
Saya biasanya mendapat data dari buku tua atau catatan surat kabar dan arsip yang menarik. Atau kejadian-kejadian di masa silam. Asal kita rajin membuka buku tua, kita akan mendapatkan banyak data. Kebetulan saya orang yang rajin mengumpulkan buku tua. Biasanya saya cari di pasar tua Semarang, Beringharjo Yogyakar ta, Palasari Bandung, Pasar di belakang stadion Sriwedari Solo, dan lain-lain. Saya kenal hampir semua pedagang buku tua di tempat-tempat itu. Dari situ saya buat catatan penting yang menarik. Utamanya yang saya tidak tahu. Nah, dari situ saya ambil sepotong-sepotong untuk memperkuat alur cerita.
(T) : Apakah alur cerita sudah Anda siapkan?
(J) : Biasanya berkembang. Mula mula memang ada outline yang disiapkan seperti Parijs van Java itu. Tapi, ada unsur tidak senga ja yang masuk kemudian. Ini justru yang menarik dalam proses penulisan. Kalau temuan baru itu menarik, saya masukkan ke dalam bagian alur cerita. Namun, tidak jarang saya mengkhianati outline yang sudah dibuat karena unsur tiba tiba itu justru lebih menarik trend-nya. Kalau sudah begitu saya harus hapus sebagian out line untuk temuan baru tadi. Tapi, secara keseluruhan tetap harus ada yang namanya klimaks sebagai pertanggungjawaban tematik dari cerita itu. Jadi, begitu saya bicara outline, saya hanya bicara potongan potongan remisnya.
(T) : Bagaimana dengan Kerudung Merah Kirmizi, apakah melalui riset pustaka juga?
(J) : Kalau itu sepenuhnya tinggal imajinasi saja.Tapi, saya sudah mengenal betul setting yang saya tulis di Rawa Selang antara CiranjangCipeyeum. Saya kenal betul desa yang di dalam. Lalu tempat terpencil di Cikarawang dekat Dermaga dan satu tempat di Bali. Saya kuasai karena saya pernah di sana. Jadi ketika saya butuhkan, saya panggil ingatan-ingatan tentang daerah itu.
(T) : Anda datang ke daerah itu sengaja untuk membuat latar belakang novel atau tujuan lain?
(J) : Sekadar datang saja dan saya hapal saja beberapa hal menarik di daerah tersebut, dari nama sungai sampai bukit.
(T) : Bagaimana Anda memadukan imajinasi dan kenyataan?
(J) : Barangkali jawabannya adalah agar lebih hidup dan seakan-akan benar terjadi. Seperti juga dalam Ca Bau Kan di mana saya harus mengidentifikasi peran. Dalam peran yang saya tulis, saya harus membuat pembenaran terhadap peran tokoh itu. Setelah ada pembenaran, saya berharap pembaca juga memberikan pembenaran atas pembenaran dari tokoh yang saya tulis bahwa tokoh itu ada. Meski begitu tetap harus ada perasaan benar atau ‘feeling of truth’ dalam membentuk tokoh tadi.
(T) : Mana yang Anda dahulukan, membentuk karakter tokoh atau jalan cerita?
(J) : Tokoh sudah harus ada dengan karakternya. Seorang tokoh bisa saja pada awalnya keras, tapi kemudian lembut dalam jangka waktu tertentu. Salah satu kesulitannya memang bagaimana membuat gambaran tokoh itu menjadi plastis. Karena itu harus ada alasan psikologis yang jadi penyebab ter jadinya perubahan. Seperti dalam cerita ‘Sam Po Kong’ yang sedang saya tulis sekarang.
Tokoh Dang Swa disusupkan alam pelayaran Cheng Ho ke Jawa. Padahal ia disusupkan di situ sebagai musuh Sam Po Kong yang tugasnya menjelek-jelekkan. Tapi, dalam pelayaran sekian bulan, ia berubah. Nah, untuk menggambarkan perubahan sikap ini harus ada alasan psikologis dan fisikal yang terjadi. Misalnya, dari pertikaian an melihat ketokohan seseorang hingga dia jadi kuat.
(T) : Artinya kisah itu perjalanan nyata yang Anda kemas dalam bentuk novel?
(J) : Memang perjalanan nyata. Sekarang bagaimana menghidupkan cerita itu dalam wacana imajinasi. Cerita tentang Sam Po Kong, semua orang mungkin sudah tahu. Sejarah sudah mencatat. Babat Tanah Jawi menulis kisah berbeda dan beragam. Saya harus memutuskan mengambil satu sudut yang realistis saja. Saya tidak mau membuat tokoh Cina ini bisa terbang segala, ha..ha.. ha...Padahal dalam kisah Cina dan Babat Tanah Jawi ada kisah memotong siluman di Cirebon.Tapi, kisah itu saya tulis sebagai sihir agar realistis. Begitu juga pembaca bisa menyaring dan melihat seberapa jauh komitmen pengarangnya.
(T) : Berapa banyak referensi yang Anda gunakan untuk menulis Sam Po Kong ini?
(J) : Sekitar 30 buku referensi. Misalnya, bagaimana perilaku seks di kerajaan Cina dan kaisar yang bangsat. Itu akan menjadi hiasan dalam dialog. Dalam setiap dialog selalu saya sertakan tamadun (kebudayaan) Cina agar tokoh yang dikisahkan memang tokoh bersejarah. Mereka mengungkapkan realistas yang dekat. Sama dengan saat kita membicarakan Ken Arok yang kita kaitkan dengan realitas terdekat.
(T) : Kenapa Anda banyak menulis cerita dengan latar belakang sejarah?
(J) : Seperti saya katakan,saya memilih tema yang tidak dikerjakan orang lain.Terutama latar belakang zaman Belanda yang sangat menarik buat saya.Bayangkan 350 tahun mereka di Indonesia. Akulturasi kita demikian panjang dengan mereka.
(T) : Sejak awal menulis Anda sudah memilih posisi itu?
(J) : Benar, sejak usia 17 tahun saya sudah memilih cerita berla tar-belakang sejarah lewat cerita Inani Keke dan Trapar Batala. Latar belakang kisah itu adalah abad ke15 antara Filipina dan Minahasa di masa Magelhaens terdampar di pulau Saebu. Lalu dia dipenjara di sana dan orang-orang Spanyol melari kan diri ke selatan sampai ditangkap orang Portugis di Tidore dan Ternate. Lalu mereka lari ke Minahasa atas bantuan Raja Bolaang Bongondo.Itu latar belakang novel-novel pertama saya dalam usia belasan tahun.
(T) : Apa yang membuat Anda tertarik pada tema sejarah sampai hari ini?
(J) : Adanya akulturasi yang menyangkut bahasa. Bukan main banyaknya kosakata Indonesia yang diambil dari bahasa asing, terutama di Sulawesi Utara. Sebagian bahasa Portugis sudah menjadi bahasa orang Manado sampai hari ini.Itu yang mem buat saya tertarik.
(T) : Bagaimana dengan proses penulisan non kreatif?
(J) : Sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya tema-nya saja tidak sama.Tiga hari lalu saya ceramah tentang inkulturasi. Untuk itu saya harus pakai data dan gunakan bahasa plakat, bahasa pengumuman, bahasa deklarasi. Artinya bahasa yang agak kaku, ha..ha..ha...
(T) : Mana yang lebih menarik antara penulisan kreatif dan bukan kreatif?
(J) : Sama saja.Tinggal bagaimana kita memilih materi saja. Saya membahas tema inkulturasi karena saya harus berbicara di depan sidang gerejawi. Tema yang saya ambil itu topik yang lenyap dalam jejak-jejak gerejawi saat ini, yakni asas ‘in kulturasi’. Ini yang saya kritik bahwa gereja di Indonesia menjadi sangat Amerika. Pada hal dasar pewartaan Injil itu adalah inkulturasi.
(T) : Selain soal tema besar tadi, apa lagi yang Anda angkat?
(J) : Begini, kepentingan manusia itu sama, yakni menangis dan tertawa. Itu bahasa universal. Tapi, itu harus dilihat dengan jujur, hati terbuka, lembut,dan hati tidak dendam bahwa akulturasi kita sebagai tiang budaya nasional berangkat dari banyak sumber. Sumber Cina, India, Arab. Lalu berpikir kritis dan rasional baru tentang perlintasan orang Barat yang ke sini.
Saya ingin melihat ada sumbangan dari hitam putih Belanda sebagai penjajah, yaitu pengajaran bahasa Indonesia dalam lembaga pendidikan kita. Ingat, itu Belanda yang mengatur. Yang memutuskan ‘lingua franca’ bahasa Indonesia menjadi bahasa administratif adalah Belanda. Ini yang saya angkat le wat cerita. Kalau lewat bahasa plakat mungkin kaku dan mengundang perdebatan, ha..ha..ha...Mungkin dengan begini jadi lebih masuk.
Kondisi Indonesia sekarang seperti Cina tahun 1930-an.Sakit orang Indonesia yang harus menyembuhkan adalah kesadaran membaca. Padahal membaca membedakan manusia dengan binatang. Jadi bukan sandang, pangan, dan papan.
(T) : Pendapat Anda ihwal ke hadiran penulis muda yang banyak bermunculan belakangan ini?
(J) : Tentu ini harus disambut gembira.Kalau ada pemikir muda harus dilihat sebagai pemikiran baru yang tidak ada se belumnya. Orang seperti Ayu, Dewi Lestari, sampai Djenar, menurut saya sangat luar biasa. Mereka itu ibarat bom yang tiba-tiba berada bersama-sama dengan lelaki.Bahkan berada di atas laki-laki. Mereka mele nyapkan kesan bahwa penulis perempuan hanya berbicara air mata dan nangis melulu seperti novel 1970an dan setelahnya.
(T) : Apa yang membedakan mereka dan perempuan penulis di masa lalu?
(J) : Sekarang kita punya kebiasaan penulis muda ini adalah anak-anak terpelajar. Coba bayangkan tahun 1970-an, yang namanya wartawan tidak harus sarjana. Asal bisa nulis meski agak ngawur-an, rajin pasti diterima.Sekarang kita melihat lebih terang pada mereka karena pendidikan tadi. Paling tidak mereka memenuhi strata tertentu dan punya penyataan sendiri ketika mereka menulis sesuatu.
(T) : Apakah trend yang mereka bawa benar-benar baru?
(J) : Apapun trend yang mereka cetuskan, saya yakin itu sesuai dengan sikap batin mereka.Sikap batin ini bisa mewujud se demikian rupa karena alat kerja mereka yang berbeda.
Dengan begitu otomatis lahir karya yang berbeda dan visi yang berbeda. Kita lihat dulu,setelah Chairil Anwar, orang selalu mengikuti pola Chairil Anwar. Baru berubah 1970-an dengan gerakan puisi mbeling .Artinya ada keberanian setelah itu. Sebelum itu semua seragam dan berkiblat pada Chairil. Kalau tidak ikut Chairil sepertinya tidak sah disebut penyair. Buat saya tidak ada alasan untuk tidak memuji penulis-penulis muda tadi.
(T) : Beberapa waktu lalu Anda mendapatkan penghargaan Khatulistiwa Award...?
(J) : Penghargaan itu yang pertama saya terima dari dalam negeri.Kalau dari luar negeri sudah beberapa kali, antara lain dari Jerman saya dapatkan medali Man of Achievement karena saya menulis Ensiklopedia Musik seorang diri. Katanya unik karena ensiklopedi biasanya ditulis tim.
(T) : Pernahkah Anda merasa jenuh atau buntu selama menulis?
(J) : Tidak sama sekali.Kalau saya jenuh, saya main musik sendiri atau melukis. Itu kebetulan bagian dari bakat saya.
(T) : Apakah Anda tergantung juga pada mood ?
(J) : Tidak juga, karena saya me nilai menulis adalah pekerjaan yang bersifat wajib. Maka, saya harus melaksanakannya. Tapi saya menulis bukan karena terpaksa, melainkan karena suka. Begitu saya suka, saya tidak merasa tersiksa.
(T) : Selain novel, apalagi yang Anda tulis saat ini?
(J) : Saya kan harus ceramah tentang teologi. Yang saya kembangkan betul sekarang adalah teologi kontekstual seperti inkulturasi. Kedua, tentang teologi apologetik yang jadi studi saya selama ini.
(T) : Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk satu karya tulis?
(J) : Tidak tentu karena penggarapannya biasanya bersambung.Seperti “Parisj Van Java” saya kerjakan sepanjang tahun ini.Sehari biasanya saya butuh waktu tiga jam.Untuk “Sam Po Kong” ini juga tidak tentu.
posted by wahyu.dhyatmika 11:37 AM
berita bermasalah itu.............
posted by wahyu.dhyatmika 10:54 AM
Aceh villagers say troops shot seven civilians including boy aged 12
by Ian Timberlake
MATAMAPLAM, Indonesia, Sept 22 (AFP) - Indonesian troops who descended on this North Aceh village shot dead seven young men including a boy aged 12, villagers said Thursday.
Anizar, 29, said her 18-year-old brother Khairurazzy Ismail was one of the dead. The victims were sleeping in the ricefields to protect the crops when soldiers arrived at 5.30 am on Wednesday, residents said.
"We found him (Khairurazzy) dead in the paddy field," Anizar said. "He was hit in the head ... all his brains came out."
She said her brother had also been shot in the shoulders and stabbed in the thigh. Troops on Monday launched a major offensive to crush the separatist Free Aceh Movement (GAM).
A weeping Anizar said her brother, who was mentally unstable, had no links to GAM. "My brother was sick and what would he want to do with a gun?"
She said she had no idea whether rebels were operating in the area. "We don't know where GAM is. We're ordinary people."
Anizar said the military described the victims as "dead rats in the field." Residents said they were asleep at the time but were woken by the shooting. They said a survivor who fled the attack had told them the victims were made to stand in a line and were then shot.
One villager who refused to be named said soldiers had hit him on the forearm and the back of the head with a chunk of wood. His head was bandaged and there was a chunk of hair missing.
Matamaplam is part of a cluster of small villages in Peusangan district, close to the town of Bireuen in North Aceh.
In Cot Batee village in the same area, residents said eight people were killed by troops on Wednesday.
An AFP correspondent who visited Cot Batee saw six of the bodies. Two had been shot through the eye. One of the villagers denied the victims were GAM members.
Military spokesman Lieutenant Colonel Yani Basuki said 10 people from four villages in the area had been shot, including a 13-year-old.
But he said they were GAM members and were shot during a clash which began with an explosion at a bridge.
"Some people say they were in the paddy when they were shot," Basuki said. "No, it was while we were chasing them to the paddy."
Indonesian troops have been accused of gross rights violations in previous campaigns in Aceh and elsewhere. They have promised to try to minimise civilian casualties this time.
it/sm/bjn
posted by wahyu.dhyatmika 10:54 AM
Friday, March 21, 2003
posted by ang 12:24 AM
Thursday, March 20, 2003
posted by ang 11:55 PM
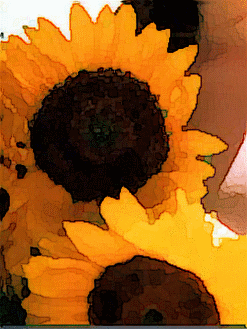
blog TOELIS, diisi oleh beberapa manusia. jika berminat untuk ikut menggunjingkan, menumpahkan, membumikan, atau mengumpatkan apa saja silakan kirim email ke anfus@frogshit.com dengan subject: ruang tulis


